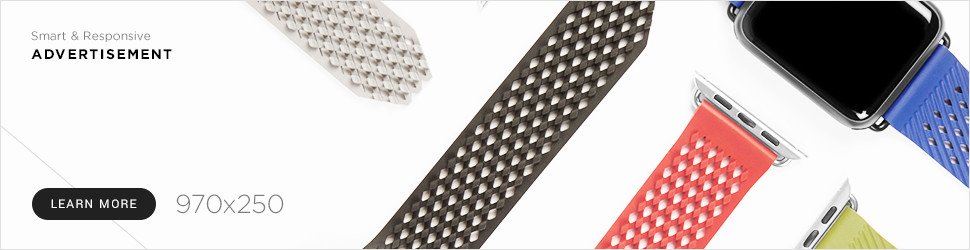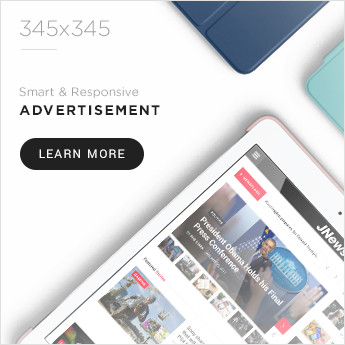JUMLAH pengaduan kasus konflik tenurial di Indonesia berdasarkan status penanganannya sejak tahun 2015 hingga November 2023, tercatat 1.583 kasus. Dari jumlah tersebut, pengaduan terbanyak terjadi di tahun 2022, mencapai 142 kasus. Provinsi Riau adalah provinsi dengan jumlah konflik tenurial tertinggi sepanjang periode tersebut dengan jumlah total 361 kasus.
Menurut Penyuluh Kehutanan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Sumatera, Fellizka Rezmiaty, jumlah pengaduan yang masuk dari Provinsi Riau memang paling banyak. Hal tersebut menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Riau melaporkan konflik tenurial cukup baik.
“Jumlah tersebut adalah jumlah laporan pengaduan yang masuk ke pusat, bukan jumlah konflik yang ada di masing-masing daerah. Boleh jadi eskalasi konflik di daerah lain banyak, tetapi angkanya tidak terlalu banyak karena pengaduan yang masuk ke kami jumlahnya sedikit,” kata Fellizka dalam diskusi bertajuk Hak Tenurial, Masyarakat Hukum Adat pada Kawasan Hutan Tanaman Industri di Riau yang ditaja Bahtera Alam di di Hotel Angkasa Garden, Pekanbaru, Rabu, 6 Desember 2023.
 Dari seluruh pengaduan yang masuk, konflik didominasi oleh objek perkebunan sawit. Itu adalah isu yang ramai di bidang agraria. “Di pekerbunan dibahas, di pertanian dibahas, di kehutanan dibahas. Ini juga yang menyebabkan kenapa di Riau mempunyai potensi konflik tenurial tinggi,” jelasnya.
Dari seluruh pengaduan yang masuk, konflik didominasi oleh objek perkebunan sawit. Itu adalah isu yang ramai di bidang agraria. “Di pekerbunan dibahas, di pertanian dibahas, di kehutanan dibahas. Ini juga yang menyebabkan kenapa di Riau mempunyai potensi konflik tenurial tinggi,” jelasnya.
Sejak tahun 2012, Indonesia sudah memiliki acuan penanganan konflik yaitu Undang Undang No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
Konflik tenurial adalah semua bentuk perselisihan atau pertentangan klaim menyangkut penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan data Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), jumlah kasus konflik tenurial di Riau yang selesai ditangani sebanyak 107 kasus. Sisanya 254 kasus, masih dalam proses penanganan. Dari total jumlah pengaduan konflik tenurial di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar dan Pelalawan adalah daerah terbanyak melakukan pengaduan, masing-masing 98 dan 60 kasus.
Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Bahtera Alam, Harry Oktavian menyebut, sengketa tenurial di Riau beberapa puluh tahun belakangan, umumnya disebabkan oleh izin konsesi untuk pembangunan wilayah perkebunan (sawit) dan kehutanan (hutan tanaman industri) yang membutuhkan penguasaan tanah dan lahan – bahkan kawasan hutan yang luas untuk kepentingan ekonomi dan bisnis.
“Sengketa tenurial berupa perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan tanah dan lahan, menjadi salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Sengketa tenurial bisa menimbulkan konflik antara berbagai pihak, seperti masyarakat adat, perusahaan, pemerintah dan LSM. Sengketa tenurial berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi dan hak asasi manusia,” kata Harry.
Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) saja di Riau, saat ini telah menguasai lahan yang sangat luas untuk penanaman akasia, bahan baku bubur kayu dan kertas. Dua perusahaan pemilik izin paling luas adalah Grup APRIL yang menguasai luas lahan lebih kurang 338.536 hektare dan Grup APP menguasai sekitar 296.373,94 hektare.
Penguasaan dan perluasan kawasan tersebut telah menimbulkan dampak negatif pada masyarakat khususnya masyarakat adat yang telah dimulai sejak awal beroperasinya perusahaan sekitar tahun 1980-an silam.
“Akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang vital untuk kehidupan mereka menjadi hilang dan ruang hidup masyarakat adat menjadi terbatas. Misalnya, gangguan terhadap tradisi, budaya, mata pencaharian, serta hak-hak tanah masyarakat adat,” kata Harry.
Sebagai contoh adalah masyarakat adat Suku Sakai yang bermukim di Kampung Mandi Angin Kabupaten Siak dan Desa Kesumbo Ampai, Kabupaten Bengkalis. Mereka adalah contoh kecil dari beragamnya masyarakat adat di Riau yang telah merasakan dampak negatif dari beroperasinya perusahaan HTI di kawasan tanah adat mereka.
Hak akses kedua kelompok masyarakat adat di atas terhadap lahan dan hutan milik mereka seakan ‘tercerabut dari akarnya,’ ruangruang hidup semakin sempit, sumber-sumber ekonomi lokal hancur hingga hilangnya kekayaan budaya seperti adat istiadat, tradisi, norma dan pengetahuan tradisional. Wujud dari persoalan dan masalah tersebut adalah munculnya konflik dan sengketa tenurial. Sengketa tenurial yang melibatkan pertentangan antara hak-hak masyarakat adat dan hak-hak yang diberikan oleh pemerintah terkait pemanfaatan lahan dan sumber daya alam menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan dan tak berkesudahan.
Harry menyebut, penting bagi masyarakat adat untuk memahami persoalan konflik tenurial dan cara penyelesaiannya. “Untuk itulah Bahtera Alam membuat diskusi dengan tujuan membangun pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat adat mengenai hak atas tanah. Dengan pemahaman yang lebih baik, dapat dicapai kesepahaman yang lebih efektif,” jelas Harry.
Selain unsur pemerintah seperti perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, KPH Bagansiapiapi dan KPH Minas Tahura yang hadir dalam diskusi, hadir pula perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Sakai Kesumbo Ampai, Sakai Mandi Angin, Suku Asli Anak Rawa dan Suku Akit Kepulauan Meranti. Dari unsur perusahaan, hadir perwakilan PT Grup APP di Riau yaitu PT Ararabadi dan unsur perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru.
Masyarakat Hukum Adat
Pada hakekatnya negara mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Pengakuan tersebut tertuang dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen 4, Pasal 18 B yang berbunyi; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dengan UU.
Ada juga regulasi penetapan status hutan adat, yaitu UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 67, putusan MK No.35/2012, UU No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat.
“Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah MHA. Tujuan penetapannya untuk menjamin ruang hidup MHA, melestarikan ekosistem (hutan dan lingkungan), perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan salah satu pola dalam penyelesaian konflik di dalam dan disekitar kawasan hutan,” kata Fellizka.
Undang Undang No.41 Tahun 1999 Pasal 67 Ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU serta mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Sepanjang tahun 2016 hingga 2023, pemerintah sudah memberikan SK penetapan hutan adat kepada 131 MHA (76.079 KK) dengan total luas lebih kurang 244.195 hektare. Jumlah tersebut berada di 40 kabupaten di 18 provinsi. Di Provinsi Riau baru ada 2 MHA di Kabupaten Kampar yang mendapat SK Penetapan Hutan Adat di tahun 2019 dengan luas 408 hektare.
Ketua MHA Suku Akit Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Suparjo saat diskusi menyampaikan keluhan tentang lahan kelola mereka yang masuk dalam konsesi perusahaan milik Grup APRIL pada tahun 2009. Sejak saat itu, mereka kehilangan mata pencarian, tidak bisa melakukan apa-apa di lahan garapannya.
“Wilayah kami sudah dibentengi oleh kanal, sehingga tidak ada lagi akses ke lahan yang dulu adalah lahan garapan kami. Apa yang harus kami lakukan?” ungkap Suparjo kepada Fellizka.
Fellizka menjelaskan, di situla fungsi dari perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
Aturan tentang perhutanan sosial ada di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaah Perhutanan Sosial.
“Kita memberikan akses kelola antara pemegang izin dengan masyarakat yang ada di dalam kawasan atau sekitar kawasan hutan. Salah satunya sebagai solusi penanganan konflik yang ada terkait pengelolaan dan penguasaan tanah. Skema pengelolaannya bisa dengan kemitraan kehutanan. Ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan masyarakat mendapatkannya,” jelas Fellizka.
Hingga 13 September 2023, total realisasi perhutanan sosial untuk lima skema mencapai luas 6.073.184,42 hektare dengan jumlah unit SK sebanyak 9.019. *
Laporan: WD Utami